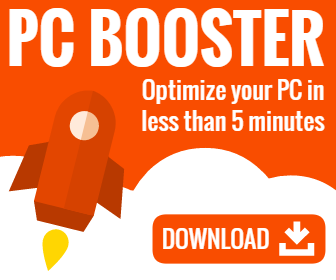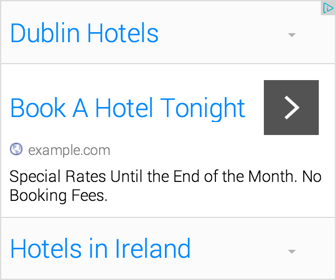SAMARINDA — Jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, publik dihebohkan oleh tren pengibaran bendera Jolly Roger—ikon bajak laut dalam serial anime One Piece. Aksi ini menuai pro dan kontra, bahkan disebut-sebut sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi pemerintahan saat ini.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyayangkan aksi tersebut. Menurutnya, pengibaran simbol dari budaya populer asing bisa menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu persatuan.
“Ini bukan sekadar bendera kartun. Ada potensi memecah belah, terutama karena simbol ini asing bagi banyak kalangan,” katanya.
Sementara itu, anggota MPR RI, Firman Soebagyo, menilai ajakan tersebut sebagai upaya yang tidak pantas dan dapat menyinggung nilai-nilai kebangsaan. “Kita tidak boleh membiarkan simbol-simbol seperti ini menggantikan makna sakral kemerdekaan,” ujarnya tegas.
Namun di sisi lain, akademisi dari Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, justru melihat fenomena ini sebagai bentuk ekspresi sosial yang patut didengar. Ia menilai, maraknya penggunaan simbol dari One Piece adalah respons dari publik terhadap dinamika politik yang mengecewakan.
“Bendera Jolly Roger ini sebetulnya bukan simbol pemberontakan fisik, tapi bentuk metaforis dari kekecewaan masyarakat yang merasa tidak didengar,” terang Saipul kepada Media Kaltim, Jumat (1/8/2025).
Saipul menjelaskan, karakter One Piece dikenal karena sikap perlawanan terhadap kekuasaan korup dan otoriter—sesuatu yang, dalam pandangan sebagian masyarakat, mencerminkan realitas politik Indonesia belakangan ini. Ia menilai kritik ini sah-sah saja, asalkan tidak disertai tindakan destruktif.
Menurutnya, masyarakat kini mulai menggunakan pendekatan simbolik untuk menyuarakan keresahan, terutama karena ruang dialog yang dinilai makin menyempit. “Mereka mencari bentuk lain untuk bersuara, salah satunya lewat simbol budaya pop,” tambahnya.
Ia juga menyoroti sederet kebijakan kontroversial seperti revisi undang-undang, pembatasan ruang digital, hingga dominasi oligarki dalam ekonomi dan politik, yang memperdalam rasa frustrasi publik.
“Pemerintah seharusnya menjadikan ini sebagai bahan refleksi. Kalau simbol seperti ini marak digunakan, artinya ada jarak emosional antara rakyat dan penguasa,” kata Saipul.
Ia menegaskan bahwa masyarakat masih mencintai negaranya, namun mulai jenuh dengan elite yang dinilai abai. Oleh karena itu, ia mendorong agar negara tidak terpancing reaktif, melainkan membuka ruang dialog dan perbaikan.